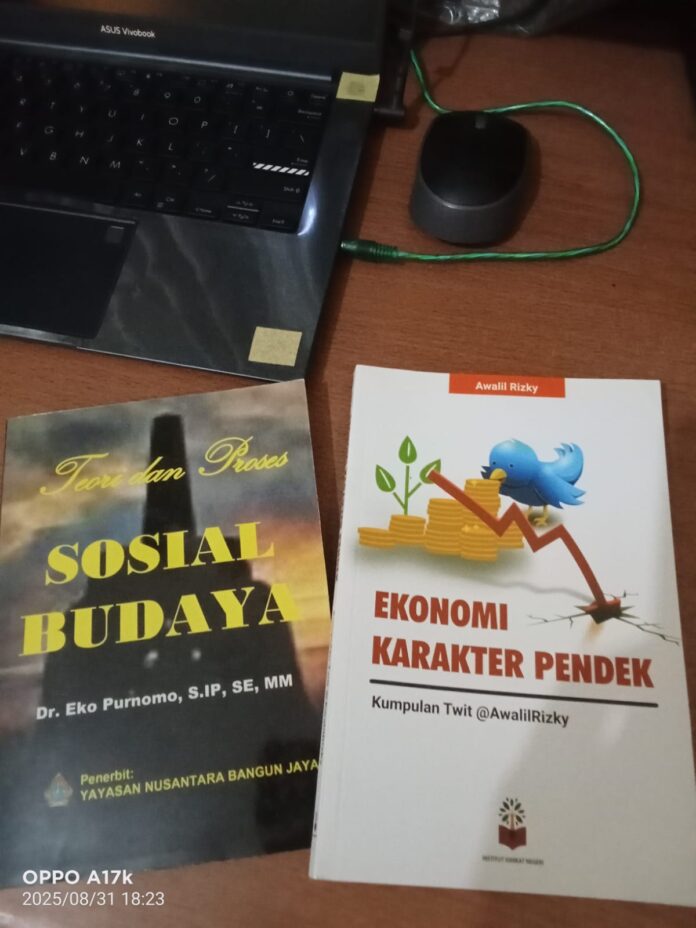Oleh: H. J. FAISAL*
Latar Belakang
Berdaulat.id, Di negeri yang katanya kaya raya dan subur makmur ini, rakyat justru tumbuh dalam keputusasaan. Negara besar, katanya. Tetapi rakyatnya kecil, ya kecil harapan hidupnya, ya kecil porsi makannya, ya kecil pula kepercayaannya kepada pemimpinnya.
Polisi, yang seharusnya menjadi pelindung, malah jadi pelindas. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga menjadi simbol betapa nyawa rakyat tidak lebih berharga dari ban kendaraan taktis.
Peristiwa 28 Agustus 2025 itu bukan sekadar tragedi, tetapi pengingat bahwa aparat bisa seenaknya, dan rakyat cuma bisa berteriak, dan menangis sambil merekam, menyaksikan semua kejadian memilukan itu di depan mata mereka langsung.
Terlepas dari anomali ditunggangi atau tidak ditungganginya akasi protes massa terhadap DPR kemarin, yang pasti korban sudah berjatuhan, perutr rakyat sudah lapar, dan rakyat sudah jenuh dengan semua ketidakbecusan kinerja para pemimpin negeri ini, dan juga jijik melihat kelakuan para artis kafiran yang duduk di kursi DPR sana.
Presiden pun muncul di layar kaca, menyampaikan pidato yang katanya menenangkan. Para ulama ketua tokoh ormas Islam pun dikumpulkan. Tidak ketinggalan juga seluruh ktua umum partai yang ada di negara ini. semuanya tiba-tiba dipeluk kembali, untuk menenangkan panasnya hati rakyat. Tetapi rakyat bukan anak TK yang bisa ditenangkan dengan dongeng. Kata-kata indah tidak bisa menenangkan hati yang sudah terlanjur kecewa, apalagi tidak bisa mengenyangkan perut, dan apalagi juga menghidupkan kembali kepercayaan yang sudah lama mati.
DPR, yang katanya wakil rakyat, malah lebih mirip kedai kopi mewah, lengkap dengan pertunjukkan ‘live song’ nya. Tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, joget-joget di sidang tahunan, dan senyum lebar saat rakyat berteriak lapar. Mereka duduk di kursi empuk, sementara rakyat duduk di trotoar, menunggu keajaiban.
Siapa Yang Bisa Dipercaya Oleh Rakyat Negeri Ini?
Lalu rakyat bertanya….siapa yang bisa menjadi pegangan kami kalau begitu?
Ulama?
Hmm… mereka lebih sibuk mengurus tender proyek yang diberikan oleh pemerintah, dan rapat internal ormas. Sibuk mencari sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup ormas yang dipimpinnya.
Bertemu presiden pun lebih mirip temu bisnis daripada temu nurani. Rakyat melihat mereka seperti melihat menara gading, tinggi sekali, tetapi jauh dan dingin.
Mungkin hanya beberapa ulama kharismatik saja yang bebnar-benar dipercaya oleh umat saat ini. Dan itu pun menjadi sebuah pertaruhan kewibawaan mereka di depan umat. Apakah umat atau rakyat akan benar-benar mau mematuhi nasihat mereka saat ini….Entahlah.
Akademisi?
Ah, yang satu ini justru lebih parah lagi. Ketika mahasiswa mereka ditembaki gas air mata, para dosen sibuk menyeduh kopi sachet di ruang dosen ber-AC. Mereka menulis jurnal tentang demokrasi, tetapi lupa bahwa demokrasi juga butuh keberanian nyata, bukan sekadar kutipan.
Di luar sana, mahasiswa berteriak. Mereka berlari, terengah, menantang gas air mata demi satu kata….keadilan. Sementara di dalam kampus, dosen-dosen sibuk mengisi formulir kenaikan jabatan fungsional sambil ngopi, membuka handphone dan laptop, dan menulis status netral…“Semoga Semua Pihak Mampu Menahan Diri.”
Mereka bukan pengecut, katanya. Mereka hanya “berpikir jernih.” Jernih seperti air kolam ikan koi yang tidak pernah terusik, meski di sekelilingnya api sudah membakar pagar.
Ketika mahasiswa ditangkap, mereka diam. Ketika mahasiswa dipukul, mereka menggeleng pelan. Jangankan untuk turun ke jalan bersama mahasiswa mereka, untuk sekedar melawan ketidakadilan melalui tulisan pun, mereka tidak mampu.
Entah karena memang tidak mampu untuk menulis atau karena takut keluar dari kandang nyamannya, atau takut akan kena tegur Rektor dan sertifikasinya akan dibatalkan oleh kementrian pendidikan tinggi.
Tetaapiii…. ketika ada regulasi baru yang memudahkan sertifikasi dosen, yang notabene hasil perjuangan mahasiswa mereka, mereka berlari paling depan, mengisi formulir, mengunggah berkas, dan menulis essai tentang “Peran Dosen Dalam Menjaga Demokrasi.” Apa tidak mantap itu, tulisan…?
Ada yang bersembunyi di balik gelar Doktor, seolah-olah gelar itu adalah jubah kebal dari tuntutan moral.
Mereka menulis jurnal tentang “Civil Society,” tetapi tak pernah sekalipun berdiri di tengah masyarakat sipil yang sedang dipukul. Mereka berbicara tentang “Agency Of Change,” tapi kehilangan keberanian untuk sekadar menyatakan: “Ini salah.”
Ironi? Tidak juga….
Ini adalah seni bertahan hidup ala akademisi Indonesia yang sudah sangat tipikal. Mereka melempar batu, lalu menyembunyikan tangan di balik jurnal bereputasi. Mereka bicara tentang etika, tetapi lupa bahwa keberanian adalah bagian dari moralitas.
Dan mungkin, satu-satunya harapan tinggal pada mereka, para dosen dan akademisi yang berani menulis, bersuara, dan berdiri.
Meskipun sendiri, meskipun dicibir, bahkan dianaktirikan oleh lingkungan akademisi lainnya, tetapi mereka akan tenang saja, karena prinsip opara dosen pemberani ini adalah bahwa suara kebenaran tidak butuh mayoritas, tetapi hanya butuh keberanian dari hati nurani yang masih hidup dan berani.
Media?
Sebagian besar sudah dikooptasi. Mereka lebih takut kehilangan iklan daripada kehilangan integritas. Kecuali beberapa yang masih berani, bukan media banci, yang tetap menulis meski tahu ancaman bisa datang kapan saja. Tetapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari, dan jari rakyat sudah terlalu lelah menghitung.
TikTok, yang sempat jadi panggung rakyat, pun ikut tiarap. Fitur LIVE ditangguhkan, katanya demi keamanan. Padahal rakyat cuma ingin bicara, ingin menunjukkan bahwa mereka ada.
Tetapi di negeri ini, bicara pun bisa dianggap ancaman. Bukan begitu…begitu bukan?
Maka rakyat pun turun ke jalan. Protes, teriak, bahkan menjarah.
Ilegal? Ya. Tetapi sah di mata nurani. Karena ketika semua saluran resmi ditutup, maka rakyat akan menciptakan saluran mereka sendiri, ya saluran rakyat namanya….meski berisiko, meski penuh luka.
Ironisnya, para pemimpin rezim juga terpilih lewat proses yang legal. Tetapi apakah mereka legitimate? Rakyat menjawab dengan diam yang penuh makna. Legalitas tanpa legitimasi hanyalah jas formal tanpa isi. Rapi di luar, kosong di dalam.
Di sinilah kita bisa mengingat Max Horkheimer (1895–1973), tokoh teori kritis, yang menyatakan bahwa tugas teori sosial bukan hanya menjelaskan dunia, tetapi membebaskan manusia dari relasi yang eksploitatif. Dia menolak pemisahan antara subjek dan objek sosial. Bagi Horkheimer, manusia bukan sekadar angka statistik, tapi pusat dari evolusi sosial.
Peter L. Berger (1929–2017) dan Thomas Luckmann (1927–2016) pun mengingatkan lewat teori konstruksi sosial bahwa realitas sosial adalah hasil dari interaksi manusia. Rakyat bukan objek yang dibentuk oleh negara, tetapi subjek yang membentuk makna sosial melalui pengalaman dan tindakan.
Dan Rasulullah Salallahu’alaihi wassalam, dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim, bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka.”.
Sebuah hadits yang menegaskan bahwa relasi pemimpin dan rakyat seharusnya bukanlah relasi atas kekuasaan, tetapi relasi berdasarkan cinta dan doa.
Sampai di sini, kita sudah paham ya….antara kondisi bernegra yang ideal dan amburadul.
Saluran ‘Short Cut’ Rakyat
Maka lahirlah gerakan sipil, jurnalisme warga, dan solidaritas horizontal. Rakyat saling memegang satu sama lain, karena tidak ada lagi yang bisa dipegang dari atas. Rakyat hanya bisa membangun ulang harapan dari puing-puing.
Dan mungkin, di suatu hari nanti, sejarah akan mencatat bahwa di tengah ketidakbecusan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian para pemimpin negara dan wakil mereka di parlemen, rakyat Indonesia memilih untuk tidak diam.
Kepemimpinan Tanpa Visi Rakyat
Maka dari itu, jangan pilih lagi pemimpin yang memang mempunyai hobi nyapres, karena begitu dia terpilih menjadi pemimpin, yang dilakukan adalah omon sana omon sini, dengan bangga menyatakan bahwa dia bisa menjadi seorang presiden, dan bukan berniat memajukan bangsa dan rakyatnya.
Apalagi terang-terangan mengatakan bahwa dia menjadi seorang presiden karena dibantu oleh presiden sebelumnya yang jelas-jelas sudah dibenci oleh rakyat.
Yakinlah…mereka yang sejak awal sudah “hobi nyapres” tersebut sering kali menjadikan jabatan bukan sebagai amanah, tetapi sebagai panggung ego.
Begitu terpilih, yang dilakukan bukan menyusun kebijakan strategis, tetapi menyusun narasi personal. Omon sana, omon sini, bicara di forum Internasional, tampil di podcast, selfie di lokasi bencana, semua demi membuktikan bahwa “Aku Bisa Jadi Presiden.” Tapi rakyat tidak butuh pembuktian, rakyat butuh pembelaan.
Ketika jabatan hanya dijadikan batu loncatan menuju ambisi pribadi, maka yang lahir adalah pemimpin yang sibuk mengelola persepsi, bukan realitas. Mereka lebih takut kehilangan popularitas daripada kehilangan kepercayaan rakyat.
Padahal, seperti kata Rasulullah Salallahu’alaihi wassalam: “Pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.”
Tetapi lucunya di negeri ini, malah pelayan yang justru minta dilayani. Beraninya bersembunyi di balik parlemen. Dan ketika para anggota parlemen DPR ‘bertingkah’ dan menari di atas penderitaan rakyat, kena batunya oleh rakyat, hingga mereka dipecat oleh ketua umum partainya, mulailah dia kelimpungan mencari dukungan organisasi rakyat ke sana-sini.
Padashal strategi mereka hanya muncul saat kampanye, minta naik gaji dan tunjangan, joged-joged, lalu menghilang saat kenyataan pahit datang.
Sejatinya, dalam teori kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin seharusnya menginspirasi, memotivasi, dan memprioritaskan kepentingan kolektif. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya….rakyat dijadikan latar belakang, bukan subjek utama.
Hobi nyapres bukanlah indikator kapasitas, melainkan obsesi. Kita butuh pemimpin yang enggan tampil tetapi rajin bekerja. Yang tidak sibuk membuktikan dirinya layak, tetapi sibuk membuktikan bahwa rakyat layak hidup lebih baik.
Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur…mudah-mudahan saja buburnya enak dimakan oleh semua. Kita lihat saja bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi rakyat setelah semua kerusuhan yang terjadi secara nasional ini.
Mudah-mudahan rakyat masih bisa makan besok, minggu depan, tahun depan, dan selamanya…..di negeri yang katanya subur makmur, gemah ripah loh jinawi ini.
Wallahu’allam bisshowab
Jakarta, 1 September 2025
*Dosen Prodi PAI, dan Pascasarjana UNIDA Bogor/ Director of Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS) / Pemerhati Pendidikan dan Sosial/ Anggota PJMI